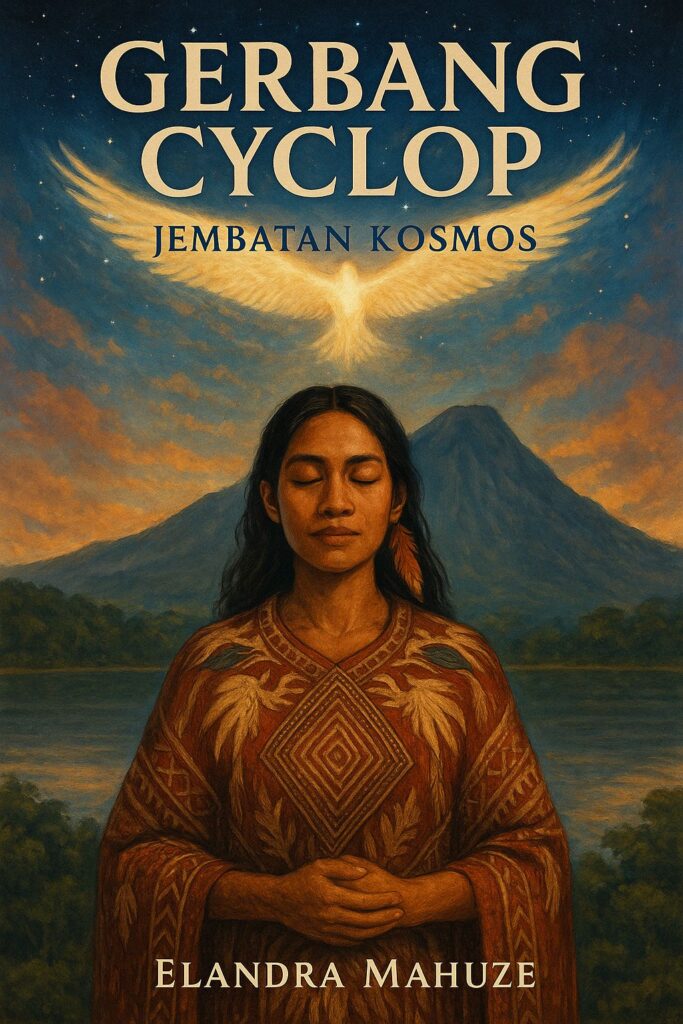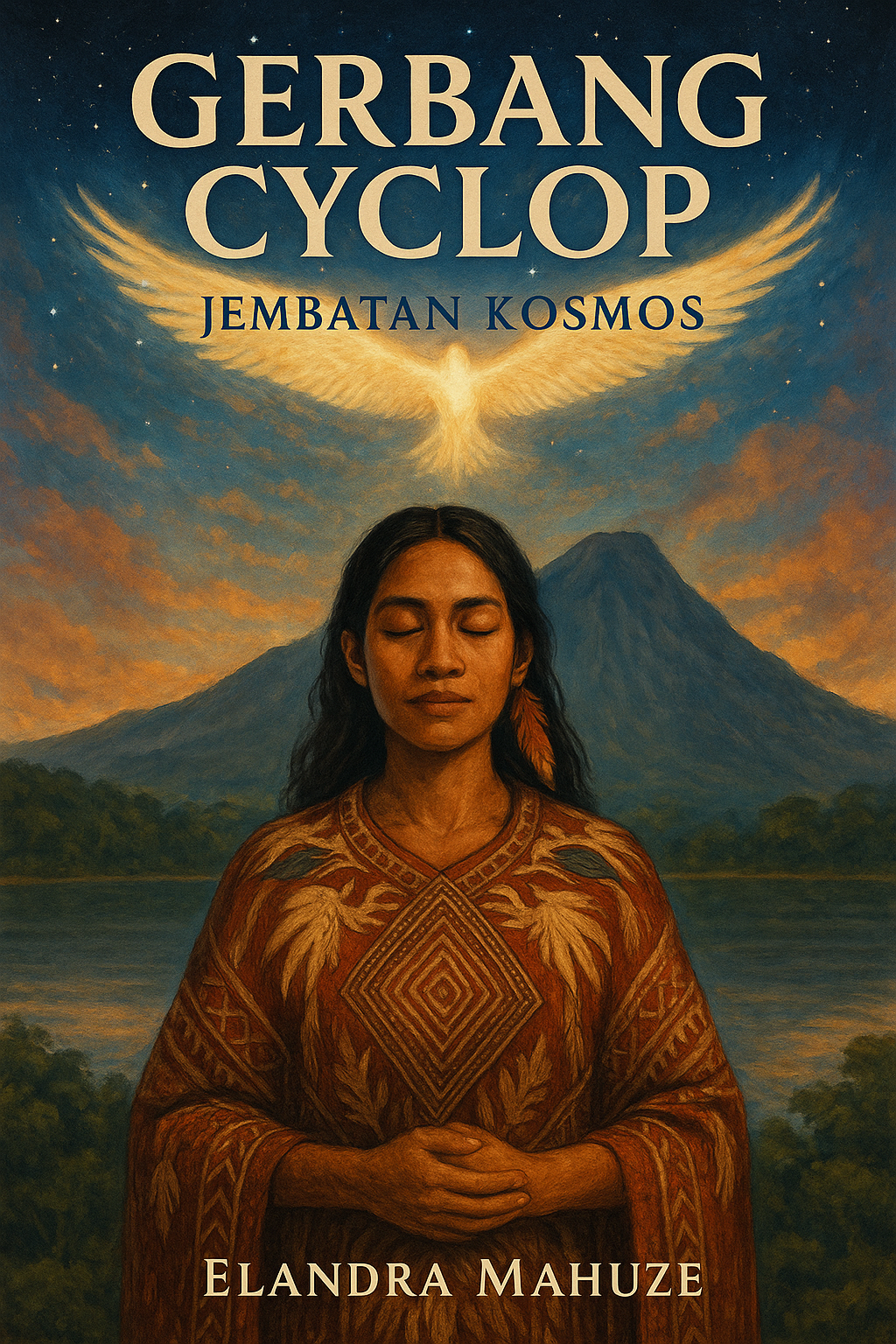Malam menyelimuti Danau Sentani seperti jubah hitam brtabur bintang. Angin membawa aroma tanah basah, daun sagu yang kering, dan bisik air yang menari lembut di tepian. Di kejauhan, Gunung Cyclop menjulang, bayangannya menggurat langit bagai penjaga abadi yang memandang kosmos. Puncaknya, tersapu awan tipis, berkilau samar di bawah sinar bulan, seolah menjadi jembatan yang menghubungkan bumi dengan rahasia langit yang tak terucap.
Di lereng gunung, di sebuah tanah datar yang dikelilingi pohon pandan dan sagu liar, seorang lelaki muda bernama Tameyo berdiri dalam keheningan. Usianya belum tiga puluh, tetapi matanya menyimpan kedalaman seorang tetua, penuh beban pengetahuan yang dititipkan leluhur. Rambutnya, diikat dengan tali kulit burung kasuari, berkibar diterpa angin malam. Jubah anyamannya, terbuat dari serat kayu dan dihiasi bulu cenderawasih, berderit pelan saat ia melangkah menuju lingkaran batu di depannya. Batu-batu megalit itu, dipahat oleh tangan-tangan kuno, tersusun dalam spiral yang menyerupai mata—mata raksasa yang menatap langit, menanti panggilan kosmos.
Tameyo adalah penjaga, keturunan garis yang dipilih sejak bumi masih menyanyikan lagu pertamanya. Malam ini, ia datang untuk mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Di tangannya, ia memegang noken, tas anyaman kecil yang menyimpan sehelai bulu cenderawasih dan sebutir kristal bening seukuran kacang kelapa. Kristal itu, kata leluhur, adalah “kunci bumi,” pecahan nyawa gunung yang hidup. Saat disentuh, ia bergetar pelan, seolah menjembatani detak jantung Tameyo dengan denyut kosmos.
Langit di atas Cyclop bergerak. Awan-awan berputar lambat, membentuk pusaran samar, dan bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah mendekat untuk menyaksikan. Tameyo menutup mata, napasnya menyatu dengan irama angin. Ia mulai bernyanyi, suaranya rendah dan bergema, seperti gemuruh air di gua purba. Lagu itu bukan miliknya; ia adalah warisan, mengalir dari mulut ke mulut, dari jiwa ke jiwa. Dalam bahasa kuno yang hanya dipahami tetua, kata-katanya menceritakan burung cahaya yang turun dari langit, membangun jembatan kosmos untuk membawa manusia pertama ke puncak gunung.
“O burung cahaya, sayapmu adalah jembatan kosmos. O penjaga langit, tanah ini adalah simpulmu. Kami menjaga, kami mendengar, kami menanti.”
Saat nyanyiannya mengalir, kristal di tangannya mulai bersinar. Cahaya lembut, biru keemasan, memancar dari dalam, menerangi wajah Tameyo yang penuh khidmat. Batu-batu megalit di sekitarnya menjawab; mereka bergetar pelan, mengeluarkan dengung rendah yang terasa seperti detak jantung bumi. Angin terhenti, dunia menjadi sunyi, hanya ada nyanyian Tameyo dan gemuruh gunung yang tersembunyi, seolah Cyclop sendiri sedang bernapas, siap menjadi jembatan ke alam lain.
Lalu, ia melihatnya—bukan dengan mata, tetapi dengan jiwa. Dalam kegelapan kelopak matanya, sebuah visi muncul. Burung cahaya, megah dan besar, sayapnya terbuat dari kilauan bintang, melayang di atas Cyclop. Tubuhnya bukan daging, melainkan energi berpulsasi, seperti denyut alam semesta. Burung itu menatap Tameyo, matanya penuh pengetahuan yang tak bisa diucapkan. Di belakangnya, langit terbelah, memperlihatkan jembatan kosmos—benang-benang cahaya tipis yang menghubungkan Cyclop dengan gunung-gunung lain di bumi: puncak bersalju di negeri jauh, dataran luas di bawah langit asing, dan lembah yang diselimuti kabut abadi. Jembatan itu hidup, bergetar, menyatukan simpul-simpul dunia dalam harmoni.
“Penjaga,” suara burung itu bukan suara, melainkan getaran yang mengalir ke tulang Tameyo. “Cyclop adalah jembatan kosmos, simpul yang menyatukan bumi dan langit. Gerbang akan terbuka kembali, bukan di masa kau, bukan di masa anakmu, tetapi saat darah penjaga bangkit di timur dunia. Ia akan bernyanyi, dan jembatan akan hidup. Ia akan melihat, dan kosmos akan menjawab. Jaga nyanyian ini, jaga kunci ini, atau dunia akan lupa jalannya.”
Tameyo membuka mata, napasnya tersengal. Kristal di tangannya kini redup, tetapi hangat, seolah baru disentuh api bintang. Di langit, pusaran awan telah lenyap, bintang-bintang kembali pada tempatnya. Namun, sesuatu telah berubah. Ia merasakan getaran di bawah kaki, denyut halus dari perut gunung. Cyclop bukan sekadar gunung; ia adalah simpul, jembatan kosmos yang menanti saatnya untuk bersinar.Dengan hati-hati, Tameyo berjalan menuju megalit terbesar di lingkaran. Di tangannya, ia memegang alat pahat sederhana, terbuat dari batu obsidian yang diasah tajam. Jemarinya bergerak dengan pasti, seolah dipandu oleh tangan tak kasat mata. Ia mengukir burung cahaya, sayapnya terentang lebar, membentuk lengkungan jembatan. Di bawahnya, ia menggambar manusia bersayap, memegang kristal yang bersinar. Dan di atas, sebuah lingkaran cahaya, simbol gerbang yang menjadi jembatan kosmos.
Saat ia selesai, langit bergemuruh. Kilat menyambar di kejauhan, menerangi Danau Sentani yang berkilau seperti cermin bintang. Dari tepian danau, penduduk kampung yang terbangun oleh gemuruh itu menatap ke arah Cyclop. Mereka melihat cahaya—bukan kilat, bukan api, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Cahaya itu melonjak dari puncak gunung, membentuk lengkungan samar seperti jembatan menuju langit, sebelum lenyap ke dalam malam.
Tameyo menoleh ke arah danau, matanya penuh tekad. Ia tahu, tugasnya bukan untuk melintasi jembatan kosmos, tetapi untuk memastikan nyanyian itu hidup. Ia menggantung noken di lehernya, kristal dan bulu cenderawasih aman di dalamnya. “Keturunanku akan menjaga,” bisiknya, suaranya menyatu dengan angin yang kembali bertiup. “Kami akan menanti.”
Di bawah langit yang kini tenang, Cyclop berdiri diam, menyimpan rahasianya. Di tepi danau, seorang anak kecil, terbangun dari mimpi, mendengar sisa nyanyian Tameyo yang terbawa angin. Ia tak mengerti kata-katanya, tetapi hatinya tahu: burung cahaya akan kembali, dan jembatan kosmos akan bersinar lagi.